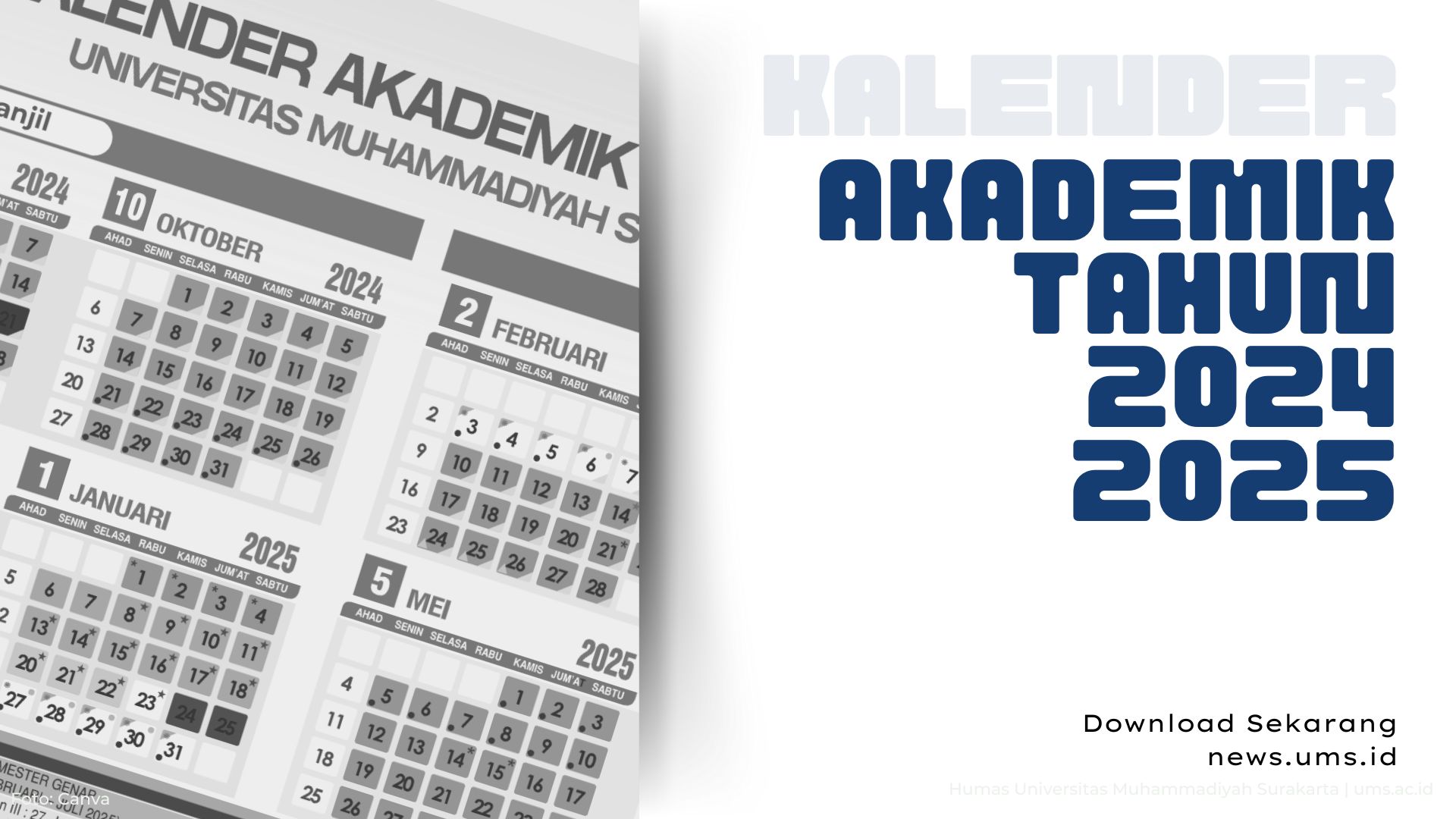ums.ac.id, SURAKARTA – Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial (PSBPS) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menyelenggarakan Kolokium Internasional bertajuk “Clothing as Self-Expression and Cultural Identity in Indonesia and Japan” dengan menghadirkan tiga pembicara dari berbagai latar belakang keilmuan dan kebudayaan.
Acara yang berlangsung pada Jumat (13/9) di Ruang Rapat BPH UMS, Lantai 6 Gedung Induk Siti Walidah ini menghadirkan tiga narasumber ini antara lain: Prof. Dr. Momo Shioya, ahli antropologi dari University of Shimane, Jepang; Prof. Sahid Teguh Widodo, Ph.D., Ketua PUI Javanologi dari Universitas Sebelas Maret (UNS); serta Dra. Yayah Khisbiyah, MA, dosen Fakultas Psikologi dan Direktur Eksekutif PSBPS UMS.
Menurut Momo Shioya, pakaian tradisional di Indonesia, seperti batik dan kebaya, bukan hanya berfungsi sebagai busana, tetapi juga sebagai simbol identitas yang kuat dalam konteks sosial dan budaya. Sebaliknya, di Jepang, kimono, yang dahulu menjadi pakaian sehari-hari, kini hanya digunakan pada acara-acara tertentu, seperti upacara pernikahan atau ritual budaya.
Salah satu aspek menarik yang dibahas oleh Shioya adalah fenomena “Kimono Police” di Jepang, yang merujuk pada orang-orang yang secara sukarela atau bahkan tidak resmi menegur mereka yang dianggap salah mengenakan kimono.
“Di Jepang, ada banyak aturan ketat terkait cara memakai kimono dengan benar, mulai dari cara melipat kain, jenis motif yang sesuai, hingga cara mengikat obi (sabuk kimono). Jika tidak dipatuhi, bisa jadi seseorang akan ditegur oleh ‘Kimono Police,’ orang-orang yang merasa bertanggung jawab melestarikan etiket mengenakan kimono secara benar,” jelas Prof. Shioya.
Aturan-aturan tersebut, menurutnya, justru membuat generasi muda Jepang enggan memakai kimono dalam kehidupan sehari-hari karena takut dianggap tidak mematuhi tata cara yang benar.
Sementara itu, narasumber kedua, Prof. Sahid Teguh Widodo, memaparkan secara rinci mengenai busana tradisional Keraton Kasunanan Surakarta. Menurutnya, busana adat Jawa, khususnya di kedaton, merupakan cerminan nilai-nilai budaya dan estetika yang diwariskan secara turun-temurun. Busana ini tidak hanya berfungsi sebagai pakaian, tetapi juga sebagai simbol status sosial dan keagamaan.
“Busana di keraton memiliki makna yang dalam, baik dari segi estetika maupun nilai spiritual. Sejak zaman Majapahit hingga Kraton Surakarta, pakaian seperti dodotan, kemben, dan semekan sudah menjadi bagian dari kehidupan para bangsawan. Busana tersebut dirancang sedemikian rupa untuk mencerminkan kehormatan dan kesopanan, sesuai dengan ajaran Islam,” ungkap Sahid.
Ia menambahkan bahwa meskipun busana-busana tersebut dianggap ‘terbuka’ menurut standar modern, pada zamannya, busana ini tidak menyalahi ajaran agama Islam karena penggunaannya terbatas di dalam lingkungan kraton dan di hadapan sesama wanita atau keluarga dekat.
Selanjutnya Dra. Yayah Khisbiyah, MA, dalam sesi terakhir, menyajikan perspektif psikologi sosial tentang pakaian, terutama dalam kaitannya dengan representasi diri dan konformitas. Ia menyoroti bagaimana pakaian, selain sebagai medium ekspresi dan representasi diri, juga bisa menjadi alat untuk menegakkan norma-norma sosial, namun juga sekaligus hierarki dalam masyarakat.
Salah satu poin yang dibahas Yayah adalah peran seragam aparat, seperti ASN dan militer, yang mencerminkan otoritas dan kepatuhan.
“Seragam bukan hanya sekadar pakaian kerja. Ia menjadi representasi otoritas, kepatuhan, kolektivitas, dan konformitas. Dalam konteks ASN dan militer, seragam juga menciptakan deindividuasi, di mana identitas pribadi menjadi kabur dan digantikan oleh identitas kelompok,” ujar Yayah.
Ia menggarisbawahi bahwa dalam struktur birokrasi, seragam berfungsi sebagai alat untuk menegakkan hirarki dan aturan-aturan ketat. Seragam dinas di Indonesia diatur dengan ketat, mulai dari model, warna, hingga waktu penggunaannya. Yayah menekankan bahwa seragam dapat menghilangkan individualitas seseorang dan menggantinya dengan identitas kolektif.
“Ketika seseorang mengenakan seragam, ada efek deindividuasi, yaitu ia cenderung mengikuti norma dan aturan yang ditetapkan oleh institusi, bahkan tanpa mempertanyakan moralitas tindakan yang dilakukan,” jelasnya.
Diskusi lintas-disipliner ini dihadiri oleh sekitar 40 peserta dari berbagai institusi, di antaranya Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Universitas Sebelas Maret, STKIP PGRI Pacitan, Universitas Gadjah Mada, Pusat Kajian Perempuan Solo (PUKAPS), mahasiswa internasional, perwakilan dari sektor ekonomi, dan berbagai pusat studi.
Yayah menjelaskan, melalui PSBPS UMS, kolokium internasional ini merupakan stepping stone untuk membuka peluang kerjasama akademik antara UMS dan the University of Shimane, Jepang, yang akan diformalisasi melalui Memorandum of Understanding (MoU). Kerjasama ini diharapkan akan memperkuat penelitian, pengajaran, publikasi ilmiah, pertukaran akademik serta mempererat hubungan lintas-budaya di kedua institusi. (Maysali/Humas)